Pengungsi ASEAN terus menjadi isu kemanusiaan yang tak kunjung mendapat penyelesaian regional yang solid. Meski ASEAN menyebut dirinya sebagai komunitas yang menjunjung tinggi kemanusiaan, dalam praktiknya krisis pengungsi laut justru menjadi potret lemahnya kerja sama regional dan minimnya keberhasilan diplomasi kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.
Daftar isi
Krisis pengungsi Rohingya menjadi sorotan utama. Ribuan orang melarikan diri dari Myanmar dan terdampar di perairan Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Namun, sebagian besar negara ASEAN menolak memberikan akses masuk. Bahkan, beberapa negara mendorong kapal pengungsi kembali ke laut tanpa bantuan.
ASEAN tidak memiliki protokol penanganan krisis pengungsi yang jelas. Situasi ini memperkuat kesan bahwa organisasi ini lebih fokus pada stabilitas politik ketimbang hak asasi manusia.
Akar Masalah Pengungsi ASEAN: Prinsip Non-Intervensi dan Kepentingan Nasional
Prinsip non-intervensi yang melekat pada Piagam ASEAN selama ini mencegah organisasi ini mengambil tindakan tegas terhadap negara anggota, termasuk Myanmar. Padahal, mayoritas pengungsi yang terdampar di perairan Asia Tenggara berasal dari negara tersebut, terutama etnis Rohingya yang mengalami penganiayaan sistematis.
Sebagai akibatnya, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia menghadapi beban sebagai negara transit dan tujuan. Sayangnya, sebagian besar dari mereka belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang membuat sistem perlindungan dan pemrosesan suaka bersifat ad hoc dan minim akuntabilitas.
Sejarah Kerja Sama yang Pernah Berhasil: Kasus Pengungsi Indocina
Menariknya, ASEAN pernah menunjukkan kapasitas kerja sama regional dalam menangani krisis serupa. Pada dekade 1970-an hingga 1990-an, ASEAN bersama PBB membentuk Comprehensive Plan of Action untuk menangani pengungsi Indocina. Melalui pendekatan burden sharing, ratusan ribu pengungsi dari Vietnam, Laos, dan Kamboja berhasil ditempatkan secara aman di berbagai negara.
Namun, pola kerja sama ini tidak dilanjutkan secara permanen dan tidak pernah diinstitusionalisasi dalam bentuk kerangka regional tetap. Krisis pengungsi Rohingya, sayangnya, tidak mendapat pendekatan serupa meski memiliki urgensi yang sama.
ASEAN sebenarnya memiliki beberapa forum dan institusi yang dapat dimanfaatkan, seperti AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management) dan Bali Process yang melibatkan negara-negara di luar ASEAN dan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM.
Namun, peran kedua forum tersebut masih terbatas. AHA Centre lebih difokuskan pada bencana alam ketimbang krisis pengungsi, sementara Bali Process belum memiliki mekanisme tanggung jawab yang mengikat dan bersifat sukarela.
Diplomasi Kemanusiaan: Inisiatif yang Terbatas
Beberapa negara anggota seperti Malaysia dan Indonesia memang telah mencoba melakukan diplomasi bilateral terkait krisis pengungsi. Malaysia, misalnya, pernah memimpin inisiatif pembicaraan repatriasi Rohingya bersama Bangladesh. Namun, langkah-langkah ini tidak cukup kuat tanpa dukungan kolektif ASEAN.
Sikap pasif Myanmar terhadap konsensus lima poin ASEAN terkait konflik internal dan penolakan terhadap dialog yang inklusif memperburuk situasi. Ironisnya, ASEAN tetap memberi ruang kepada junta militer di forum regional, mengurangi tekanan moral dan diplomatik yang bisa saja menjadi pendorong perubahan kebijakan.
ASEAN cenderung menyerahkan tanggung jawab penanganan pengungsi kepada lembaga internasional seperti UNHCR, IOM, dan berbagai LSM. Ini memperlihatkan ketidaksiapan internal untuk membentuk sistem respons regional yang mandiri dan berkelanjutan. Padahal, beban geopolitik dan reputasi internasional ASEAN semakin besar, terutama dengan meningkatnya jumlah pengungsi iklim dan konflik bersenjata di masa mendatang.
Harapan Terbaik
- Reformasi Prinsip Non-Intervensi
ASEAN perlu mulai merevisi interpretasi prinsip ini agar tidak menjadi penghalang dalam penanganan isu lintas batas seperti pengungsi. - Pembentukan Task Force Khusus
ASEAN sebaiknya membentuk gugus tugas regional untuk pengungsi dan migrasi, bekerja sama dengan AHA Centre dan organisasi internasional. - Ratifikasi Konvensi Internasional oleh Negara Anggota
Dorongan diplomatik agar negara-negara transit seperti Malaysia dan Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 menjadi penting untuk menciptakan standar perlindungan minimum. - Pemanfaatan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)
Meski tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini bisa menjadi dasar moral untuk mengembangkan kebijakan bersama yang lebih humanis.
Krisis pengungsi laut di kawasan ASEAN merupakan isu yang kompleks dan menyentuh berbagai dimensi: kemanusiaan, politik, dan hukum. Namun yang jelas, pendekatan saat ini belum cukup. Jika ASEAN ingin tetap relevan sebagai komunitas politik dan keamanan, maka kerja sama regional dan diplomasi kemanusiaan bukan hanya harus diperkuat tapi juga diinstitusionalisasi secara tegas dan kolektif.
Reff Sites:
- https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-takes-asean-mantle-tempers-expectations-myanmar-south-china-sea-2025-01-18/
- https://apnews.com/article/bangladesh-malaysia-yunus-anwar-59c33187e4f6152af362c6e46084c014
- https://www.unhcr.org/emergencies/rohingya-emergency
- https://www.hrw.org/news/2025/06/12/asia-pacific-asylum-seekers-still-facing-deadly-sea-rejections
- https://www.baliprocess.net/







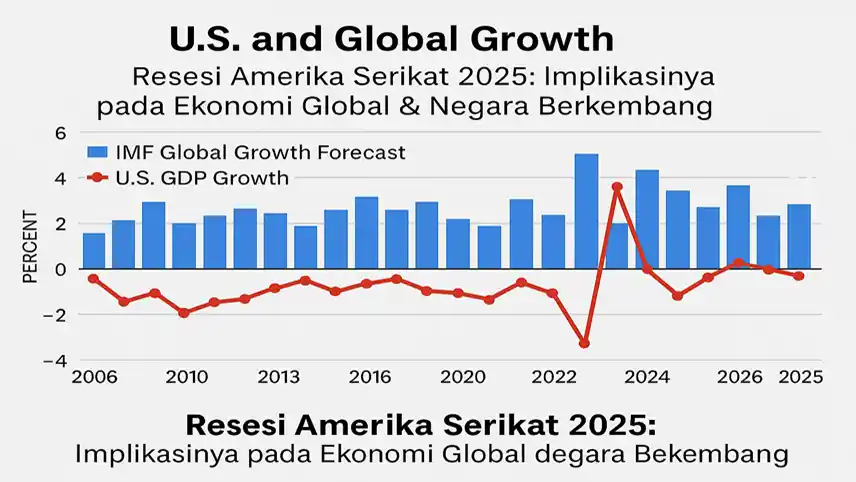
Tinggalkan Balasan